Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pesantren jika disandingkan dengan
lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia merupakan sistem pendidikan
tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous.
Pendidikan ini awalnya merupakan pendidikan agama islam yang dimulai sejak
munculnya masyarakat islam di nusantara pada abad XIII. Beberapa abad kemudian
penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat
pengajian (“nggon ngaji”). Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian
tempat-tempat menginap bagi para pelajar atau para santri, yang kemudian
disebut pesantren.Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu
pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstuktur,
sehingga pendidikan pesantren dianggap sangat bergengsi.
Sebagai lembaga pendidikan, pesantren
mengiringi dakwah islamiyah di Indonesia yang memiliki persepsi plural dan
ponpes juga dipandang sebagai agen pengembangan masyarakat, dimana persiapan
sejumlah konsep kurikulum dan pengembangan SDM sangat diharapkan untuk
peningkatan kualitas ponpes itu sendiri maupun peningkatan kehidupan
masyarakat.
B. Kerangka Teoretik
1. Terminologi dan Sejarah Pesantren
Istilah pesantren bisa disebut dengan
pondok saja atau dua kata ini disebut dengan pondok pesantren. Secara esensial
semua makna ini mengandung makna yang sama kecuali ada sedikit perbedaan.
Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai
pembeda antara pondok dan pesantren. Secara terminologi K.H. Imam Zarkasyi mengartikan
pesantren sebagai lembaga pendidikan islam dengan system asrama atau pondok
dimana kyai sebagai figure sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang
menjiwainya, dan pengajaran agama islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti
santri sebagai kegiatan utamanya.
Pondok pesantren menurut M. Arifin
adalah suatu lembaga pendidikan agama islam yang tumbuh secara diakui
masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri
menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang
sepenuhnya di bawah kedaulatan dari leadershipseorang atau beberapa orang kyai
dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala
hal. Lembaga Research Islam mendefinisikan pesantren sebagai suatu tempat
pendidikan dan penagajaran yang menekankan pelajaran agama islam dan disdukung
asrama sebagai temapta tinggal snatri yang bersifat permanen.
Dilihat dari bentuk dan sistem yang
ada, pesantren disinyalir merupakan model pendidikan yang diadopsi dari India.
Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem dan model tersebut telah
digunakan di India, baru kemudian pada zaman Hindu Budha di Jawa, model atau
sistem tersebut digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran di
kerajaan-kerajaan di Jawa.
Pada awal Islam di Indonesia,
pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang didalamnya
terjadi interaksi antara kyai atau ustadz sebagai guru dan para santri sebagai
murid. Pelaksanaan pengajarannya bertempat dimasjid atau halaman-halaman pondok
(asrama).Sedangkan materi pengajarannya adalah buku-buku teks keagamaan karya
ulama klasik atau lebih dikenal dengan kitab kuning.
Keberadaan pesantren yang survive dan
berkembang sejak jauh sebelum kemerdekaan menjadikan inspirasi untuk
memasukkakn pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemampuan
untuk tetap survive lebih disebabkan bahwa ada tradisi lama yang hidup
ditengah-tengah masyarakat Islam dalam segi-segi tertentu masih relevan. Model
pendidikan pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan yang berbasiskan
masyarakat sebab maju berkembang atau mundurnya serta kepemilikannya diserahkan
sepenuhnya kepada masyarakat.Namun seiring dengan tuntutan zaman, pesantren
kini telah melakukan abanyak perubahan dan pembaruan.Selain pesantren
mengajarkan pendidikan agama beberapa pesantren kini juga telah mengembangkan
komponen-komponen pendidikan lainnya, baik dalam bentuk pendidikan formal
maupun non formal seperti keterampilan, kesenian, bahasa asing, dan pendidikan
jasmani. Pesantren dalam perkembangannya jikan dilihat dari sarana fisik yang
dimilikinya dapat dikelompokkan menjadi lima macam tipe, yaitu:
a.
Tipe
pertama, pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kyai.
b.
Tipe
kedua, pada tipe ini selain adanya masjid dan rumah kyai didalamnya telah
tersedia pula bangunan berupa pondokan atau asrama bagi para santri yang datang
dari tempat jauh.
c.
Tipe
ketiga, tipe ini pesantren telah memiliki masjid, rumah kyai, serta pondok. Didalamnya
diselenggarkan pengajian dengan metode sorogan, bandongan, dan sejenisnya.
Selain itu pada pesantren tipe ini,
telah tersedia sarana lain berupa madrasah atau sekolah yang berfungsi sebagai
tempat untuk belajar para santri baik ilmu umum maupun agama.
d.
Tipe
keempat, pesantren tipe ini selain telah memiliki pondok, masjid, ruamah kyai,
juga telah dilengkapi dengan tempat pendidikan untuk pengembangan keterampilan
seperti lahan untuk peternakan dan pertanian, tempat untuk membuat kerajinan,
koperasi dan laboratorium.
e.
Tipe
kelima, pada tipe ini pesantren telah berkembang sehingga disebut pula sebagai
pesantren modern. Selain adanya masjid, rumah kyai dan ustadz, pondok,
madrasah, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lainnya seperti perpustakaan,
dapur umum, aula, ruang makan, kantor, toko, wisma (penginapan untuk tamu) ,
tempat olahraga, bengkel, balai kesehatan, taylor, market dan lain lain.
Menurut Zamakhsari Dhofier bentuk dan
model pondok pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua: Pertama pondok
pesantren salafi yaitu pondok pesantren yang inti pendidikannya tetap
mempertahankan pengajaran klasik. Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan
sistem sorogan yang merupakan bentuk pengajian model lama dengan tidak
memperkenalkan pengajaran umum.
Kedua, pondok pesantren khalafi,
ialah pondok pesantren yang dalam pengajarannya telah memasukkan mata pelajaran
umum dalam madrasah yang dikembangkannya atau sekolah umum di lingkungan pondok
pesantren, seperti pondok pesantren Gontor yang tidak lagi mengajarkan
kitab-kitab klasik (kuning), tetapi santri tetap diharuskan dapat memahami
kandungan kitab-kitab klasik tersebut dengan menggunakan kaedah-kaedah bahasa
Arab yang telah dipelajari. Akhirnya terlepas dari pengelompokkan tipe-tipe
pesantren tersebut, sebuah institusi dapat disebut pesantren apabila memiliki
sekurang-kurangnya tiga unsur pokok, yaitu: kyai yang memberikan pengajian,
santri yang belajar dan tinggal dipondok dan masjid sebagai tempat ibadah dan
tempat ngaji.
2. Fungsi Pesantren
Dari waktu ke waktu fungsi pesantren
berjalan secara dinamis, berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial
masyarakat global. Betapa tidak, pada awalnya lembaga tradisional ini
mengembangkan fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.
Sementara Azyumardi Azra menawarkan adanya tiga fungsi pesantren, yaitu:
a.
Transmisi
dan trnsformasi ilmu-ilmu islam
b.
Pemeliharaan
trdisi islam
c.
Regenerasi
ulama
Dalam perjalanannya hingga saat ini,
sebagai lembaga sosial, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal baik
berupa sekolah umum maupun sekolah agama (madrasah,sekolah umum, dan perguruan
tinggi). Disamping itu, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non formal
berupa madrasah diniyah yang mengajarkan bidang-bidang ilu agama saja.
Pesantren juga telah menegembangkan funsinya sebgai lembaga solidaritas sosial
dengan menampung anak-anak Dari segala lapisan masyarakat muslim dan memberi
pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan tingkat socsal ekonomi
mereka.
Bahkan melihat kinerja dan charisma
kyai, pesantren cukup efektif memainkan peran sebagai perekat hubungan dan
penagyom masyarakat, baik pada tingkatan local, regional, dan nasional.Dengan
berbagai peran yang potensial yang dimainkan oleh pesantren, nampakanya dapat
dikemukakan bahwa pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan
masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan moral (reference of morality)
bagi kehidupan masyarakat umum.
3. Prinsip-Prinsip Pesantren
Menurut K.H. Imam Zarkasyi dalam
seminar Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Kehidupan dalam pondok pesantren
memiliki prinsip-prinsip yang dijiwai dalam Panca Jiwa Pondok Pesantren yang
diantaranya yakni :
a. Jiwa
Keikhlasan. Pendidikan Pesantren tidak karena didorong oleh keinginan
memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, melainkan semata-mata karena untuk
ibadah. Dalam hal ini Kyai ikhlas dalam mengajar, para santri ikhlas dalam
belajar, masyarakat atau lingkungan ikhlas dalam membantu.
b. Jiwa
Kesederhanaan. Kesederhanaan mengandung unsure kekuatan atau ketabahan hati,
penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup dengan segala kesulitan.
c. Jiwa
Kesanggupan Menolong Diri Sendiri atau Berdikari. Berdikari dalam hal ini bahwa
santri dapat berlatih mengurus kepentingannya sendiri dan mandiri, sedangkan
Pondok Pesantren sendiri sebagai Lembaga Pendidikan yang tidak pernah
menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan orang lain.
d. Jiwa
Ukhuwwah Islamiyah. Kehidupan di Pondok Pesantren diliputi suasana persaudaraan
yang akrab, sehingga segala sesuatu dirasakan bersama dengan jalinan perasaan
keagamaan. Jiwa ukhuwwah ini yang mempengaruhig persatuan ummat dalam
masyarakat
e. Jiwa
Bebas. Bebas dalam berfikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depannya,
dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri, dengan
berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi
kehidupan. Dan kebebasan ini harus berada dalam garis-garis yang
positif, dengan penuh tanggung jawab.
4. Kurikulum Pesantren
Kurikulum pesantren seperti yang
diungkapkan oleh Saylor bersama Alex-ander meliputi kagiatan-kegiatan
intra-kulikuler dan ekstra-kulikuler, dan bisa melibatkan di samping aktivitas
yang diperankan oleh santri dan juga kyai.
Ketika masih berlangsung di langgar (surau) atau masjid, kurikulum pengajian
masih dalam bentuk yang sederhana, yakni berupa inti ajaran Islam yang
mendasar. Rangkaian trio ajaran islam yang berupa iman, islam dan ihsan.
Penyampaian tiga komponen ajaran Islam tersebut dalam bentuk yang paling
mendasar, sebab disesuaikan dengan tingkat intelektual dengan masyarakat
(santri) dan kualitas keberagamaannya pada waktu itu. Peralihan dari langgar
(surau) atau masjid lalu berkembang menjadi pondok pesantren ternyata membawa
perubahan materi pengajaran. Dari sekedar pengetahuan menjadi suatu ilmu. Dari
materiyang hanya bersifat doctrinal menjadi lebih interpretative kedati dalam
wilayah yang sangat terbatas. Mahmud Yunus mencatat, “ilmu yang mula-mula
diajarkan di pesantren adalah ilmu sharaf dan nahwu, kemudian ilmu tafsir, ilmu fiqih, tafsir,
ilmu kalam (tauhid), akhirnya sampai kepada ilmu tasawuf dan sebagainya.
Di masa sekarang, menurut istilah Abdurrahman Wahid, sistem pendidikan di
pesantren tidak didasarkan pada kurikulum yang digunakan secara luas, tetapi
diserahkan pada penyesuaian yang elastis antara kehendak kyai dan santrinya
secara individual.
5. Metode Pembelajaran Pesantren
Dalam rangkaian system pengajaran,
metode menempati urutan sesudah materi (kurikulum). Penyampaian materi tidak
berarti apapun tanpa melibatkan metode. Metode selalu mengikuti materi, dalam
arti menyesuaikan dengan bentuk dan coraknya, sehingga metode mengalami
transformasi bila materi yang disampaikan berubah. Akan tetapi, materi yang
sama dapat dipakai metode yang berbeda-beda. Kategori pesantren tradisional dan
modern ternyata mengakibatkan perubahan metode. Departemen Agama RI melaporkan
bahwa metode penyajian atau penyampaian di pesantren ada yang bersifat
tradisional seperti wetonan (bandongan), sorogan, muhawarah, dan mudzakarah. Dan ada pula metode yang bersifat non
tradisional (metode berdasarkan pendekatan ilmiah).
Simpulan
Pesantren sebagai lembaga pendidikan
islam dengan system asrama atau pondok dimana kyai sebagai figure sentral,
masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama islam di
bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Azyumardi
Azra menawarkan adanya tiga fungsi pesantren, yaitu:
a.
Transmisi
dan trnsformasi ilmu-ilmu islam
b.
Pemeliharaan
trdisi islam
c.
Regenerasi
ulama
Kehidupan dalam pondok pesantren
memiliki prinsip-prinsip yang dijiwai dalam Panca Jiwa Pondok Pesantren yang
diantaranya yakni : Jiwa keikhlasan, Jiwa kesederhanaan, Jiwa berdikari, Ukhuah
islamiyah, Jiwa bebas.
Mahmud Yunus mencatat, “ilmu yang
mula-mula diajarkan di pesantren adalah ilmu sharaf dan nahwu, kemudian ilmu tafsir, ilmu fiqih, tafsir,
ilmu kalam (tauhid), akhirnya sampai keada ilmu tasawufdan sebagainya. Di masa
sekarang, menurut istilah Abdurrahman Wahid, sistem pendidikan di pesantren
tidak didasarkan pada kurikulum yang digunakan secara luas, tetapi diserahkan
pada penyesuaian yang elastis antara kehendak kyai dan santrinya secara
individual. Departemen Agama RI melaporkan bahwa metode penyajian atau
penyampaian di pesantren ada yang bersifat tradisional seperti wetonan
(bandongan), sorogan, muhawarah, dan mudzakarah. Dan ada pula metode yang
bersifat non tradisional (metode berdasarkan pendekatan ilmiah).
Daftar Pustaka
Arifin, Imron. 1993. Kepemimpinan Kiai Kasus Pondok Pesantren
Tebuireng. Malang: Kalimasahada.
Departemen Agama RI.
1984/1985. Seri Monografi Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok
Pesantren. Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren.
Hidayat, Ara, &
Machali, Imam. 2012. Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam
Mengelola Sekolah dan Madrasah. Yogyakarta: Kaukaba.
HS, Mastuki. 2005.
Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka.
Qomar, Mujamil. 2005.
Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta:
Erlangga.
Wahid, Abdurrahman.
Bunga Rampai Pesantren. Jakarta: CV. Dharma Bakti.
Wiryosukarto, Amir
Hamzah. 1996. Biografi K.H. Imam Zarkasyi. Dari Gontor Merintis Pesantren
Modern. Ponorogo: Darussalam Press.
Yunus, Mahmud. 1985.
Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.
Zarkasyi, Imam. 1930.
Diktat Kuliah Umum Pondok Modern Darussalam Gontor. Ponorogo: Darussalam Press.
Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip dan
Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah (Yogyakarta: Kaukaba. 2012),
hlm. 294-296.
Mastuki HS, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm.
90-91.
K.H. Imam Zarkasyi, Diktat Kuliah Umum Pondok Modern Darussalam
Gontor (1930), hlm. 11-14.
Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia
(Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), hlm. 232.
Abdurrahman Wahid, Bunga Rampai Pesantren (Jakarta: CV.
Dharma Bakti, t.t.), hlm. 101.

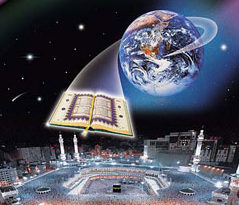


Comments
Post a Comment