Dalam
konteks sistem ketatanegaraan masing – masing negara menganut sistemnya
sendiri. Seperti pada hal nya Indonesia yang memilih untuk menjadi negara yang
berdemokrasi dan berdaulat berdasarkan atas hukum (rechsstaat) dengan sistem
pemerintahannya yang berdasarkan atas sistem konstitusi hukum. Dalam
mengartikan demokrasi, tidak hanya memberikan dengan satu konsep saja,
melainkan banyak konsep dari berbagai kalangan untuk memberikan arti demokrasi
itu sendiri.
Secara
sederhana, demokrasi sendiri mempunya hakikat yang di dalamnya terdapat suatu
kebebasan, kesetaraan, keterbukaan, etika, dan norma kehidupan yang harus
dijunjung tinggi oleh warga negara nya. Untuk arti demokrasi dalam pandangan
yang sangat sederhana dan umum bagi khayalak sekitar yaitu berarti demokrasi
merupakan bentuk opini publik yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (government of the people, by the people, and
for the people).
Negara
Kesatuan Repubilk Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi akan
demokrasi tehadap seluruh rakyatnya. Berdasarkan hukum dan sistem pemerintahan
Indonesia yang tidak bersifat absolut dan tetap atas dasar konstitusi,
Indonesia menjadi negara yang berdemokrasi. Indonesia menjadikan UUD 1945
sebagai dasar demokrasi, dengan kata lain adalah demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, sistem demokrasi merupakan
sistem yang dianggap unggul dalam membentuk suatu negara. Adnya demokrasi
merupakan suatu tindakan yang menghargai perbedaan serta kebegragaman nilai
suatu masyarakat di dalam suatu negara. Dengan demokrasi, sebagai warga negara
dapat mengemukakan pendapat nya dengan bebas
yang tentunya diikuti oleh batasan norma tertentu.
Jika
melihat perspektif pendidikan dengan demokrasi merupakan komponen yang sangat
penting dalam suatu organisasi masyarakat. Pendidikan yang mampu mengembangkan
pemikiran kritis, kreatif, dan cermat yang dapat memberikan ilmu dalam praktik
berdemokrasi di dalam kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan
demokrasi dalam pendidikan dalam rangka mewujudkan kecerdasan sosial yang
demokratis merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di
Indonesia.
1.2.1
Bagaimana konsep demokrasi di Indonesia ?
1.2.2
Apa prinsip demokrasi di Indonesia ?
1.2.3
Apa indikator demokrasi di
Indonesia ?
1.2.4
Bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia ?
1.2.5
Bagaimana pendidikan demokrasi di Indonesia ?
1.3.1
Untuk mengetahui konsep demokrasi di Indonesia
1.3.2
Untuk mengetahui prinsip demokrasi di Indonesia
1.3.3
Untuk mengetahui indikator demokrasi di Indonesia
1.3.4
Untuk mengetahui perjalanan demokrasi di Indonesia
1.3.5
Untuk mengetahui pendidikan demokrasi di Indonesia
2.1
Konsep Demokrasi
di Indonesia
Kata
“demokrasi” selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sipil apalagi di kalangan
politisis serta menjadi konsumsi publik sehari-hari di negri kita ini. Di
samping itu, demokrasi seolah-olah tidak lagi menjadi hal yang ambigu, apalagi kran demokrasi melalui reformasi 1998
dibuka seluas-luasnya, dan siapapun bisa mengakses untuk mengamati dan terjun
langsung didalamnya.
Dalam
perjalanan sejarah bangsa, demokrasi sebenarnya sudah lama di anut oleh nenek moyang kita dari dahulu. Akan tatapi,
dalam parjalananya kemudian demokrasi tidak jarang menuai beragam hambatan atau
bahkan ancaman salah satu ancaman terbesar yang sedang di hadapi oleh demokrasi Indonesia adalah
keputusan terhadap demokrasi itu sendiri yang belum berbanding lurus dengan
tujuannya, serta melemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan
kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang anti
demokrasi.
Indonesia
mengalami kehidupan politik yang demokratis tidak terlalu lama. Kehidupan
politik demokrasi itu hanya berlangsung antara tahun 1950-1959. Lemahnya pra-syarat sosial-ekonomi dan
infrastruktur ikut mempengaruhi pendeknya usia
demokrasi. Demikian pula, tipologi elit politik nasional yang ada belum tertranformasikan dari disunified elite ke consensually unified
elite-suatu kondisi yang menyulitkan tercapainya kesepakatan-kesepakatan
yang dinegosiasikan di antara mereka. Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami
pasang–surut sejak lahirnya Republik ini hingga sekarang. Secara singkat,
pasang-surut demokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan tingkah laku para
elitnya. Apakah mereka berhati lapang, atau malah berhati sempit dan tidak
bertanggungjawab. Sikap miopik dan parokial ini terutama bersumber pada kondisi
lemahnya kultur ke-negarawaan-an yang diendap sebagian besar politisi di
Indonesia.
Indonesia
termasuk sebagai bangsa yang beruntung karena sejak awal mayoritas rakyatnya
telah memiliki sistem demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir.
Penduduknya yang mayoritas muslim hampir tidak ada yang alergi terhadap
demokrasi, berkat didikan yang di berikan oleh para pemimpinnya (founding fathers). Kenyataan ini
merupakan modal penting untuk dikembangkan lebih secara bertanggung jawab.
Adapun buahnya masih belum seperti yang diharapkan karena kesalahan dan
kelemahan dalam memimpinnnya.
1.
Pengertian Demokrasi
Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat)
semula dalampemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri
memiliki dan menjalankan seluruh politik.
Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang
paling baik dari sekian banyak sistemmaupun ideologi yang ada dewasa ini.
Menurut
para pakar hukum tata negara M.Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi
sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama
hampir negara yang ada di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas
yang fundamentalis; kedua ,demokrasi
sebagai asa kewarganegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan
masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.
Wacana
demokrasi yang berkembang saat ini ada yang telah dijadikan sebagai sistem
negara di Indonesia,merupakan hasil dari reduksi dari pemikira atau pendapat
para filsuf dari Plato hingga pasca Renaissance. Pandangan beberapa filsuf
tentang demokrasi, adalah sebagai berikut:
a. Plato memandang demokrasi dekat tirani, dan cenderung menuju tirani.
Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terbentuk dari semua
pemerintah yang tidak mengenal hukum.
b. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat
ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot, dua yang lain adalah
tirani dan oligarki.
c. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial
dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya
demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung, termasuk Locke sendiri tetap
menganut monarki terbatas.
d. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan, lebih suka monarki
konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal
adalah demokrasi klasik yang dibangun atas kebajikan kewarganegaraan. Ia
berkeyakinan pula bahwayang ideal itu tidak akan tercapai.
e. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Menurutnya,
bentuk pemerintahan mesti di dasarkan
pada aneka macam pengkajian historis. Bersamaan dengan itu,analisis dan
penegasannya pada kebebasan menunjang pemikiran demokratis.
f. Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar
pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan”
yang kekuasaanya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak
sengaja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas
penindasaan oleh mayoritas.
Secara
etimologi “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “demos” yang artinyarakyat atau penduduk suatu tempat dan”cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata demos cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara di mana
dalam sistem pemerintahanya kedaulatannya berada di tangan rakyat , kekuasaan
tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa , pemerintahan
rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.
Sedangkan
pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi adalah seperti yang
dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:
a. Joseph A. Schemer mengatakan
demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan
politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan
kompetitif atas suara rakyat;
b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana
keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak
langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang di berikan secara bebas oleh
rakyat biasa.
c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai
suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka
yang telah terpilih.
Dari beberapa pandangan dan pengertian di
atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam
sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan
kekuasaan oleh rakyat.
2.2
Prinsip Demokrasi di Indonesia
Prinsip-prinsip
demokrasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Jika kita mengungkap kembali
prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan Sukarna (1981) di atas, menunjuk pada
prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain, misalnya Robert
Dahl (Zamroni, 2011: 15) yang menyatakan terdapat dua dimensi utama demokrasi,
yakni: kompetisi yang bebas diantara para kandidat, dan partisipasi bagi mereka
yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan dua prinsip demokrasi
tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama
yakni keadilan (equality) dan
kebebasan (freedom).
Franz Magnis Suseno (1997: 58), menyatakan
bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para
pakar, ada 5 (lima) ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni: negara
hukum, pemerintah berada dibawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang
bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Hendra
Nurtjahyo (2006: 74-75) merangkum sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan
para ahli dengan menyatakan adanya nilainilai yang substansial dan nilai-nilai
yang bersifat prosedural dari demokrasi. Kedua ketegori nilai tersebut baik
subtansial dan prosedural sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai
tersebut, demokrasi tidak akan eksis, yang selanjutnya dikatakan sebagai
prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut,
yakni: kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara
mayoritas (rakyat).
Pendapat
yang sejenis dikemukakan oleh Maswadi Rauf (1997: 14) bahwa demokrasi itu
memiliki dua prinsip utama demokrasi yakni kebebasan/persamaan (freedom/equality) dan kedaulatan rakyat
(people’s sovereignty).
a.
Kebebasan/persamaan (freedom/equality)
Kebebasan
dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana
mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa
adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan
adalah pembatasan kekuasaan kekuasaan penguasa politik.
Demokrasi
adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi
tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya
merupakan pelembagaan dari kebebasan.
Persamaan
merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan,
setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan
kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi
berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus
diperlakukan sama pula dalam pemerintahan.
b.
Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)
Konsep
kedaulatan rakyat pada hakekatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat
dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal.
Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua,
terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan. Perwujudan lain
konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena
demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik
penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali rakyat maka ada dua kemungkinan
buruk pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan,
kedua, yang lebih buruk kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan
penguasa.
Sementara
itu, APA (ASEAN People’s Assembly)
mendaftar sejumlah prinsip dasar demokrasi yangditerima sebagai seperangkat
aturan main bersama dalam upaya melakukan penilaian proses demokratisasi di
kawasan Asia Tenggara, terlepas dari banyak perdebatan reotik antara demokrasi
universal dan particular, antara konsep “Barat” dan “Timur” atau “Cara
Asia/ASEAN” dan berbagai
macam
kata sifat yang tercantum di depan definisi demokrasi saat digunakan untuk
menggambarkan karakteristik demokratis sebuah negara, seperti:
semi-demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi elektoral, dan lain-lain.
Demokrasi
pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam
menjalankan perannya secara aktif dan
menentukan
dalam proses politik. Partisipasi adalah elemen
penting dalam pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya
berupa ‘mencoblos’ dalam pemilihan
umum/pemilihan kepala daerah yang
dilaksanakan secara rutin. Partisipasi menjamin keterlibatan dalam proses Kebijakan,
baik dengan melibatkan LSM, partai politik, maupun jalur-jalur lain.Tetapi,
semua ini harus didasarkan pada asumsi bahwa hak-hak untuk berpartisipasi itu memang
sudah eksis dan
masyarakat/ warganegara memiliki kapasitas dan
sumber-sumber daya yang layak utk berpartisipasi,
dan pemerintah telah
menyediakan jalur-jalur
dan institusi-institusi politk (di mana
melalui semua itu masyarakat bisa berpartisipasi).
1.
Inklusivitas/ Pelibatan
Setiap
individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain setiap individu diperlakukan
sebagai warganegara (inclusion)
terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama,
bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas dan keberagaman, juga
mengelola keberagaman tersebut
tanpa kekerasan. Demokrasi
tidak bisa eksis jika perolehan hak-hak
dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor-sektor masyarakat yang termarjinalisasi
melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif utk bisa mencapai kesamaan status dan pemberdayaan.
Kebijakan
afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka/stereotip. Perwakilan/Representasi
(Representation) Dengan
mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam
setiap proses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara absolut mengingat
keterbatasan waktu dan
ruang, jalur yang
paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat untuk
representasi/perwakilan.
Mereka
yang telah mendapatkan
mandat untuk menjalankan aspirasi
populer harus mampu mewakili konstituensi mereka. Institusi-institusi harus pula mencerminkan
komposisi sosial dari para pemilih,
baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Terlebih lagi, mereka harus mewakili
arus utama dari opini publik.
2.
Transparansi
(Transparency)
Karena
demokrasi berarti bahwa institusi-institusi
publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yang memungkinkan
masyarakat utk mengawasi dan
mengawal institusi-institusi
publik tersebut. Masyarakat atau
kelompok yang
ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan utk mempertanyakan kinerja dan kerja institusi-institusi publik tersebut. Terlebih lagi, segala informasi
mengenai proses kerja dan
kinerja mereka harus bisa dijangkau oleh publik dan media massa.
2.3
Indikator Demokrasi di Indonesia
Kerangka kerja
penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan APA yang diinspirasi konsep yang
dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi. Beetham
menerjemahkan “kedaulatan rakyat” (rule
of the people) secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol popular (popular control) dan faktor kesetaraan
politik (political equality).
Kontrol populer
memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan
mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap
masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan
dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara
dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan
kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan
(Christine Sussana Tjhin, 2005: 11-13, 19-21). Kerangka kerja utama dibagi
menjadi 3 komponen utama. Pertama, kerangka kerja hak-hak Warga Negara
yang Kesetaraannya Terjamin (Guaranteed
Framework of Equal Citizen Rights). Termasuk didalamnya adalah akses pada
keadilan dan supremasi hukum,
juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang
memungkinkan masyarakat untuk memperoleh/menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini
terdiri dari 2 tema, yaitu: Kewarganegaraan
yang Setara (Common Citizenship), dan hak-hak Sipil dan
Politik (Civil and Political Rights).
Komponen kedua, Institusi-institusi Pemerintah yang Representatif dan Akuntabel
(Institutions of Representative and
Accountable Government).Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan
adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan control populer atas
pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk
juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat
publik (yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu). Komponen kedua
terdiri dari 6 tema, yaitu: Pemilu yang Bebas dan Adil (Free and Fair Elections), partai
Politik yang Demokratis (Democratic
Political Parties), hubungan
Sipil-Militer (Civil-Military Relations),
Transparansi dan Akuntabiltas Pemerintahan (Governmental Transparency and Accountability, supremasi Hukum (Rule of Law), dan desentralisasi (Decentralization).
Komponen ketiga adalah
Masyarakat yang Demokratis atau Sipil (Civil
or Democratic Society). Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi,
asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif dan forum-forum lainnya yang
bebas dan pluralistik. Kebebasan
dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi popular dalam setiap proses
politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik
dan terselenggaranya pelayanan public yang lebih efektif. Komponen ketiga
mencakup 2 tema, yaitu: media
yang Independen dan Bebas (Independent
and Free Media), dan partisipasi
Populer (Popular Participation).
Setiap
10 tema tersebut berisikan seperangkat indicator penilaian yang dikategorikan
berdasarkan 3 dimensi, yaitu: dimensi legal, institusional dan kinerja (performance). Dimensi legal untuk
mengindentifikasi kahadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk
tema terkait. Dimensi institusional menggali ada atau tidaknya perangkat
institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat
hukum. Dimensi kinerja mengelaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam
dua dimensi sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan
proses demokratisasi berdasarkan konteks tema terkait. Indikator-indikator
dalam setiap dimensi tersebut dihrapkan dapat menjadi semacam petunjuk-petunjuk
praktis dalam proses penilaian demokratisasi
2.4
Perjalanan Demokrasi di Indonesia
Dalam
sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial
dan politik yang demokratis dalam masyarakat.Masalah ini berkisar pada
penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi serta character
and nation building dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan
timbulnya diktator perorangan, partai atau militer.
Perkembangan
demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode:
pertama, periode 1945 - 1959; kedua, periode 1959 - 1965; ketiga,
periode 1965 - 1998; keempat, periode 1998 - sekarang.
a.
Periode 1945-1959 (Masa
Demokrasi Parlementer)
Demokrasi
parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya,
persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor
dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Sistem
parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan
kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang
cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer
member peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Undang-Undang
Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif
terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta
mentri-mentrinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi
partai-partai politik usia kabinet pada pada masa ini jarang dapat bertahan
cukup lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah. Hal ini
mengakibatkan destabilisasi politik nasional.
Faktor-faktor
semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai yang
tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara
untuk undang-undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden
mengeluarkan Dekrit Presiden5 juli yang menentukan berlakunya kembali
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dasar demokrasi berdasarkan sistem
parlementer berakhir.
b.
Periode 1959-1965 (Masa
Demokrasi Terpimpinn)
Demokrasi
terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih
menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan
dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh
komunis dan peran ABRI sebagai unsure sosial-politik semakin meluas.
Undang-Undang
dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama
sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang
mengangkat Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan
pembatasan waktu lima tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.
Selain itu banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir.Soekarno
sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum,
padahal dalam penjelasan Undang-Undang dasar 1945 secara eksplisit ditentukan
bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
Selain
perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui
penetapan presiden (penpres) yang memakai dekrit presiden sebagai sumber hukum.
Partai politik dan pers yang sedikit menyimpang dari “rel revolusi” tidak
dibenarkan, sedangkan politik mercusuar dibidang hubungan luar negeri dan
ekonomi dalam negeri telah mnyebabkan keasaan ekonomi menjadi tambah seram. G
30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa
demokrasi Pancasila.
c.
Periode 1966-1998 (Masa
Demokrasi Pancasila Era Orde Baru)
Demokrasi
pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem
presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan Tap
MPRS/MPR dalam rangka untuk
meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa
Demokrasi Terpimpin, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominant
terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa
ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat
itu sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai
pancasila.
Pada
tahun 1966 pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde
Baru bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan
orde hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan
melenyapkan rezim lama. Soeharto kemudian melakukan eksperimen dengan
menerapkan demokrasi Pancasila. Inti demokrasi pancasila adalah menegakkan
kembali azas Negara hukum dirasakan
oleh segenap warga Negara, hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun
aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan
secara institusional.
Sekitar
3 sampai 4 tahun setelah berdirinya Orde Baru menunjukkan gejala-gejala yang
menyimpang dari cita-citanya semula. Kekuatan – kekuatan sosial-politik yang
bebas dan benar- benar
memperjuangkan demokrasi disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan sehingga
menjadi kekuatan yang tidak lagi mempunyai komitmen sebagai kontrol sosial.
Pada masa orde baru budaya feodalistik dan paternalistik tumbuh sangat subur.
Kedua sikap ini menganggap pemimpin paling tahu dan paling benar sedangkan
rakyat hanya patuh dengan sang pemimpin. Sikap mental seperti ini telah
melahirkan stratifikasi sosial, pelapisan sosial dan pelapisan budaya yang pada
akhirnya memberikan berbagai fasilitas khusus, sedangkan rakyat lapisan bawah
tidak mempunyai peranan sama sekali. Berbagai tekanan yang diterima rakyat dan
cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang tidak pernah tercapai,
mengakibatkan pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan dan kahirnya
mengalami keruntuhan.
Menurut M Rusli
Karim rezim Orde Baru ditandai oleh :
·
Dominannya peran ABRI.
·
Birokratisasi dan
sentralisasi pengambilan keputusan politik.
·
Pengembirian peran dan
fungsi partai politik.
·
Campur tangan
pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik.
·
Masa mengambang.
·
Monolitisasi ideologi
Negara.
·
Inkorporasi lembaga non
pemerintah.
Tujuh
ciri tersebut menjadikan hubungan Negara dengan masyarakat secara
berhadapan-hadapan, dimana Negara atau pemerintah sangat mendominasi.Dengan
demikian nilai-nilai demokrasi juga belum ditegakkan dalam demokrasi Pancasila
Soeharto.
d.
Periode 1999- sekarang
(Masa Demokrasi Pancasila Era Reformasi)
Pada
masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat
berkembang. Pelaksanaan demokrasi setelah Pemilu banyak kebijakan yang tidak
mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian
kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, model
demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Melalui
gerakan reformasi, mahasiswa dan rakyat indonesia berjuang menumbangkan rezim
Soeharto. Pemerintahan soeharto digantikan pemerintahan transisi presiden
Habibie yang didukung sepenuhnya oleh TNI. Orde Baru juga meninggalkan warisan
berupa krisis nasional yang meliputi krisis ekonomi, sosial dan politik.
Agaknya pemerintahan “Orde Reformasi” Habibie mecoba mengoreksi pelaksanaan
demokrasi yang selama ini dikebiri oleh pemerintahan Orde baru. Pemerintahan
habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di indonesia dengan jalan kebebasan
pers (freedom of press) dan kebebasan berbicara (freedom of speech). Keduanya
dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya
kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembanganya
Demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden
Abdurahman wahid sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat
signifikan sekali dampaknya, dimana aspirasi-aspirasi rakyat dapat bebas
diutarakan dan dihsampaikan ke pemerintahan pusat. Ada satu hal yang membuat
indonesiadianggap Negara demokrasi oleh dunia Internasional walaupun negara ini
masih jauh dikatakan lebih baik dari Negara maju lainnya adalah Pemilihan
Langsung Presiden maupun Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Mungkin
rakyat indonesia masih menunggu hasil dari demokrasi yang yang membawa
masyarakat adil dan makmur secara keseluruhan.
Runtuhnya
rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di
Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut
menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi
merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan
kemana arah demokrasi yang akan dibangun. Selain itu dalam fase ini pula bias
saja pembalikan arah perjalanan bangsa dan Negara yang akan menghantar
Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada periode
orde lama dan orde baru.
Sukses
atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor
kunci yakni : (a) komposisi elit politik, (b) desain institusi politik, (c)
kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non
elite, dan (d) peran civil society (masyarakat madani). Keempat faktor tersebut
harus berjalan sinergis sebagai modal untuk mengonsolidasikan demokrasi. Karena
itu seperti yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra langkah yang harus dilakukan
adalah dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup
reformasi dalam tiga bidang besar.Pertama, reformasi sistem (constitutional
reform) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan
perangkat legal sistem politik.Kedua, reformasi kelembagaan (constitutional reform empowerment) yang
menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga
politik.Ketiga,pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang
lebih demokratisDemokratisasi di
Indonesia agaknya tidak dapat dimundurkan lagi. Proses suksesi kepresidenan
dengan jelas menandai berlangsungnya proses transisi ke arah demokrasi, setelah
demokrasi terpenjarakan sekitar 32 tahun pada rezim Soeharto engan “demokrasi
Pancasilanya” dan 10 tahun pada masa rezim Soekarno dengan “demokrasi
terpimpinnya”. Dengan demikian secara jelas demokrasi yang sesungguhnya di
Indonesia belum dapatterwujud.Karena itu membangun demokrasi merupakan
pekerjaan rumah (PR) dan agenda yang sangat berat bagi pemerintah.
Dalam
kerangka itu upaya membangun demokrasi (Indonesia) dapat terwujud dalam tatanan
Negara pemerintahan Indonesia bila tersedia delapan faktor pendukung yakni :
(1) Keterbukaan sistem politik, (2) Budaya politik yang jujur dan baik, (3)
Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan, (4) Rakyat yang terdidik,
cerdas dan berkepedulian, (5) Partai politik yang tumbuh dari bawah, (6)
Penghargaan terhadap hukum, (7) Masyarakat sipil (masyarakat madani) yang
tanggap dan bertanggung jawab, dan (8) Dukungan dari pihak asing dan pemihakan
pada golongan mayoritas.
2.5
Pendidikan Demokrasi di Indonesia
Sebagai negara yang
berdemokrasi, yaitu negara Indonesia harus melakukan pendidikan demokrasi untuk
warga negaranya. Warga Negara Indonesia dapat memiliki sikap yang demokratis
dan tidak apatis terhadap negaranya jika kita belajar untuk berdemokrasi dalam
negara. Pendidikan demokrasi sangat diperlukan negara maupun warga negaranya.
Karena, pendidikan demokrasi akan memberikan wawasan luas mengenai dunia
demokrasi seperti pada hal nya kebebasan berpendapat di depan umum yang
mengutamakan hak dan kewajiban seseorang serta mengetahui bahwa adanya
persamaan kedudukan di depan hukum. Selain memberikan pengenalan yang umum
terhadap berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan juga
menjadi suatu hal yang wajib untuk setiap warga negara yang sesuai dengan kemampuannya.
1.
Hakikat Pendidikan
Demokrasi
Pendidikan demokrasi adalah upaya
sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu
warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep,
prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam
masyarakat.
Pendidikan demokrasi dapat memberikan bekal bagi setiap warga negara dalam
menghadapi dunia demokrasi yang sesuai dengan perannya di elemen masyarakat.
Pendidikan demokrasi pada
hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi nilai – nilai demokrasi kepada warga
negara agar dapat dipelajari dan diterapkan dengan baik. Pendidikan demokrasi
secara umum bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berperilaku demokratis
terhadap negaranya yang berpengatahuan dan memiliki kesadaran akan adanya nilai
– nilai demokrasi terhadap berbangsa dan bernegara.
Pendidikan demokrasi dapat
diterapkan ketika pendidikan formal berlangsung yaitu melalui sarana
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam berdemokrasi prosesnya tidak
dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita, namun harus ditunjangi dengan
pembelajaran yang berpotensi untuk membangun pengetahuan dan kesadaran
demokrasi di Indonesia. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat
memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pendidikan
demokrasi, karena secara etimologis antara lain mengembangkan nilai kesadaran
untuk menegakkan negara hukum.
Pendidikan kewarganegaraan
demokrasi juga dilaksanakan bukan hanya negara yang maju saja di negara yang
sedang berkembang juga diterapkan. Namun, sebagian negara menganggap bahwa
pendidikan demokrasi sangat penting tetapi dalam kenyataannya sering dianggap
enteng atau diabaikan. Demokrasi tidak sepenuhnya dapat dipelajari sendiri.
Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan
dihayati dengan baik oleh warga negara, sulit diharapkan mereka mau berjuang
untuk mempertahankannya.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus mengerti
akan pentingnya belajar mengenai demokrasi yang manfaatnya juga dirasakan oleh
negara maupun diri kita sendiri.
Pada akhirnya, dari pandangan
tersebut dapat diperlukan pendidikan yang baik dan memungkinkan warga negara
mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang
demokratis.
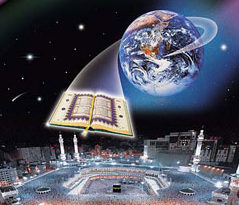


Comments
Post a Comment