PENDAHULUAN
Negara ialah suatu
organisasi atau badan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur
perihal yang berhubungan dengan sebuah kepentingan masyarakat luas serta
mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan suatu
kehidupan bangsa. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pengertian
negara, unsur negara, fungsi negara, dan tujuan negara.
Definisi konstitusi
adalah aturan dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara. Kedudukannya
merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi memiliki dua sifat yaitu
kaku dan luwes. Adapun fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan dan
menjamin HAM. Isinya berupa pernyataan luhur, struktur dan organisasi negara,
jaminan HAM, prosedur perubahan, dan larangan perubahan tertentu. Konstitusi
yang pernah berlaku di Indonesia terdiri dari 1. UUD 1945 (Konstitusi I), 2.
Konstitusi RIS 1949, 3. UUDS 1950, 4. UUD 1945 Amandemen. Amandemen konstitusi
terdiri dari pengertian, hasil-hasil dan sikap yang seharusnya positif-kritis
dan mendukung terhadap proses Amandemen UUD 1945.
1.
Negara
Negara adalah organisasi tertinggi diantara
sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk
bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang
berdaulat. Negara adalah suatu perseriktan yang melaksanakan suatu pemerintahan
melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa dalam
suatu wilayah masyarakat tertentu yang membedakan dengan kondisi masyarakat
dunia luar untuk ketertiban sosial.
1.1. Teori Terbentuknya Negara
Yang dimaksud dengan teori
terbentuknya negara adalah bagaimana perpindahan dari keadaaan manusia yang
semula hidup bebas, belum teratur ke keadaan bernegara dengan kehidupan manusia
yang serba teratur atau adanya hukum. Terbentuknya negara dapat dilihat dari
dua pendekatan, yaitu pendekatan faktual dan teoritis. Pendekatan faktual
didasarkan padakenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan dapat diungkapkan
dari pengalaman atau sejarah. Menurut sejarah, negara dapat terbentuk karena:
a.
Suatu daerah belum ada yang menguasai, diduduki
oleh suatu bangsa
b.
Beberapa negara mengadakan peleburan dan menjadi
satu negara baru
c.
Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas
bekas wilayang negara itu timbul negara baru.
Melalui
pendekatan teoritis, terbentuknya negara ditentukan melalui pendugaan-pendugaan
berdasarkan kerangka pemikiran yang logis atau bersifat hipotetik. Ada beberapa
teori terbentuknya negara, yaitu:
a.
Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles)
Menurut Plato, negara itu timbul
karena adanya kebutuhan dam keinginan manusia yang beraneka macam yang
mengharuskan mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Kesatuan mereka
inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.
Menurut Aristoteles, negara
terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang lenih
besar, kelompok itu bergabung hingga menjadi desa, dan desa bergabung lagi
menjadi kota atau negara.
b.
Teori Ketuhanan
Segala sesuatu di dunia ini
adanya atas kehendak Tuhan, juga negara pada hakikatnya ada atas kehendak
Tuhan. Penganut teori ini adalah Friedrich Julius Stahl yang menyatakan bahwa
negara tumbuh secara berangsur-angsur
melalui proses bertahap mulai dari keluarga menjadi bangsa dan negara.
Sisa-sia teori ketuhanan yang masih dapat dilihat dalam UUD berbagai negara
adalah:’berkat rahmat Tuhan’ atau ‘by the grace of God’.
c.
Teori Perjanjian Masyarakat
Teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa negara
diciptakan atas kemauan rakyat melalui perjanjian masyarakat. Pertama,
perjanjian antar kelompok manusia menyebabkan terjadinya negara, disebut pactum
unionis. Kedua, perjanjan antarkelompok manusia dengan penguasa yang diangkat
dalam rangkaian pactum unionis dinamakan pactum subjectionis, yaitu pernyataan
manusia untuk menyerahkan hak-haknya kepada penguasa dan berjanji akan taat
kepadanya.
1.2. Unsur Negara
Unsur-unsur negara ada yang
bersifat konstitusi dan ada yang bersifat delaratif. Unsur negara yang bersifat
konstitusi adalah:
a. Wilayah
b. Rakyat
c. Pemerintahan
Sedangkan
unsur negara yang bersifat deklaratif adalah sebagai berikut:
a.
Adanya tujuan negara
b.
Undang-undang dasar
c.
Pengakuan negara lain
d.
Menjadi anggota perhimpunan bangsa-bangsa
1.3. Bentuk Negara
Ditinjau dari susunanya, ada dua bentuk negara
yaitu sebagai berikut:
a.
Negara kesatuan adalah negara yang tidk tersusun
dari beberapa negara, sifatnya tunggal, hanya ada satu negara, tidak aada negara
dalam negara, hanya satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai
kekuasaan tertinggi. Negara kesatuan yang menyelenggarakan pembagian daerah
disebut negara kesatuan desentralisasi, sebaliknya negara kesatuan yang tidak
menyelenggarakan pembagian daerah disebut negara kesatuan sentralisasi,
b.
Negara federasi adalah negara yang tersusun dari
beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu
mengadakan ikatan-ikatan kerjasama, tetapi masih ingin mempunyai
wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri.jadi, tidak semua urusan diserahkan
kepada pemerintah federal. Ikatan kerjasama tersebut dapat bersifat erat dan
bersifat renggang. Berdasarkan sifaft hubungan antara pemerintah negara federal
dengan negara-negara bagian, negara federasi dapat dibedakan menjadi negara
serikat dan perserikatan negara. Apabila kedaulatan ada pada negara federasi,
yang memegang kedaulatan adalah pemerintah federal sehingga negara federasi itu
disebut negara serikat. Apabila kedaulatan itu masih ada pada negara-negara
bagian, negara federasi tersebut disebut perserikatan negara.
1.4.
Bentuk Negara Indonesia
Indonesia
sebagai suatu negara telah menegaskan dirinya dalam konstitusi negara sebagai
sebuah Negara kesatuan yang berbentuk republik, konsekwensi dari diambilnya
konsepsi tersebut adalah pengakuan sekaligus penataan dirinya sebagai sebuah
negara kesatuan (eenheidsstaat) sekaligus juga sebagai sebuah negara
hukum (rechtsstaat). Negara Kesatuan mengacu pada konsep negara yang
tata pemerintahannya dikelola satu sistem pemerintahan secara hierarkhis tanpa
mengenal adanya negara dalam negara. Adapun konsep negara hukum merujuk pada
satu bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara yang didasarkan pada dasar
konstitusional dan tertib hukum dengan menempatkan hukum sebagai satu-satunya
koridor penyelenggaraan kekuasaan dan kepentingan dalam kehidupan bernegara.
Pemahaman
bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik itulah yang
mendasari penataan dan pelaksanaan sistem desentralisasi atau yang lebih dikenal
dengan konsep otonomi daerah selama ini. Adanya konsep otonomi daerah sebagai
sebuah proses pemencaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada wilayah
dan/atau daerah-daerah yang lebih kecil adalah konsekwensi logis dari
pelaksanaan konsep negara hukum yang demokratis dalam sebuah negara yang tidak
mengenal adanya negara bagian. Pemencaran kekuasaan tersebut pada prinsipnya
adalah cara bagi sebuah negara untuk meminimalisir penggunaan kekuasaan yang
berlebihan oleh pusat, yang dapat berujung pada munculnya kekuasaan negara
absolut.
Pengkajian terhadap sistem
otonomi daerah di suatu negara hanya dapat dilaksanakan dengan benar dan
komprehensif jika dilandasi oleh pemahaman yang benar dan lurus terhadap
pilihan konsep negara yang dianut oleh negara tersebut. Untuk itu kajian atas
bentuk negara kesatuan dan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia
berikut kiranya bermanfaat sebagai pintu untuk memahami dasar pilihan
diterapkannya desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia.
1. Negara Kesatuan Indonesia.
Konsep
negara kesatuan adalah konsep bentuk negara paling tua dalam sejarah
kenegaraan, karena sampai dengan abad pertengahan hanya dikenal bentuk negara
kesatuan sebagai satu-satunya bentuk negara, adapun federasi sebagai padanan
bentuk negara baru ada dan baru dikenal sejak lahirnya Amerika serikat sebagai
satu negara merdeka.
Konsep
negara kesatuan merujuk pada bentuk negara yang hanya mengenal satu kedaulatan,
berasal dari rakyat dan berada di tangan negara (kedaulatan berada pada tangan
pusat), dengan tidak mengenal adanya negara-negara bagian yang berdaulat.
Penajaman makna dapat dilakukan dengan pembandingan dengan konsep negara
federal dengan menggunakan rumus negatif, yakni apa yang menjadi ciri negara
federal adalah negasi dari bentuk negara kesatuan.
Konsep
negara kesatuan yang pada pada awalnya memberi andil atas lahirnya pemerintahan
negara yang totaliter dan otoritarian, dalam perkembangannya seiring dengan
tuntutan demokratisasi yang mengharuskan adanya pembagian kekuasaan negara,
maka lahirlah ide unitarisme yang terdesentralisasikan, sebagaimana kita kenal
sekarang dengan istilah otonomi daerah.
Konteks ke-Indonesiaan, Pilihan
bentuk negara kesatuan sebagaimana terdapat dalam Bab I UUD 1945, merupakan
hasil permufakatan para pendiri bangsa ini pada saat awal perumusan negara dan
juga konstitusi negara. Ada beberapa alasan yang disampaikan terkait dipakainya
konsep negara kesatuan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh M. Yamin dimuka
sidang BPUPKI berikut ;
“Negara
serikat tidaklah kuat, tidak berwarna dan djuga tidak dapat didjamin kekuatan
atau keteguhannja didalam kegontjangan zaman sekarang dan untuk zaman damai …
apabila negara hendak dibentuk diseluruh tanah Indonesia setjara negara
serikat, maka dengan sendirinja federalisme jang boleh timbul oleh karena
pembentukan negara serikat itu … pulau-pulau lain akan kekurangan kaum
terpeladjar, dan negara federalistis tidaklah dapat dibentuk, karena tenaga
untuk itu tidak ada….”3
Dari
nukilan pidato tersebut, dapat difahami bahwa berdasar pertimbangan historis,
filosofis dan faktual negara Indonesia tidak memungkinkan untuk dibentuk dengan
berdasar pada faham federalistik. Disamping juga besarnya desakan dari angkatan
muda saat itu untuk mengesampingkan federalisme dan membentuk satu eenheidsstaat.
Konsep
Negara kesatuan Indonesia sendiri dapat digali dari UUD 1945 yang kendati telah
diamandemen beberapa
kali tetapi tetap teguh, dan bahkan semakin memperteguh konsepsi Indonesia
sebagai satu eenheidsstaat, sebagaimana ketentuan dalam Bab XVI tentang
Perubahan Undang-undang Dasar, Pasal 37 ayat (5) bahwa “Khusus mengenai
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Dapat Dilakukan Perubahan”.
Merujuk
pada sejarah perumusan UUD 1945, maka konsep negara kesatuan Indonesia
sejatinya lahir sejak sumpah pemuda 28 Oktober 1928 yang juga merupakan hari
lahirnya Bangsa Indonesia, sehingga unitarisme itu merupakan falsafah hidup
bangsa.
Muhammad
Yamin memaknai konsepsi negara kesatuan secara lebih luas dan mendalam sebagai
kesatuan bangsa, kesatuan tanah air dan kesatuan negara, yang berarti penolakan
terhadap faham federalisme yang bernegara bagian, dengan mengingati pula bahwa
dalam unitarisme itu dijalankan sebuah bentuk pemerintahan demokratis dan
berkeadilan, yang dijelmakan dengan adanya pembagian kekuasaan baik yang
bersifat vertikal (otonomi daerah) maupun horisontal.
Pandangan
M Yamin tersebut secara konstitusional selaras dengan ide dasar pembagian
kekuasaan secara vertikal yang termuat dalam ketentuan dalam Bab VI, Pasal 18
UUD 1945 (sebelum amandemen) tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan
bahwa:
“
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.
Pernyataan
“…dalam sistem pemerintahan negara”, menunjukkan bahwa di Indonesia
hanya dikenal satu sistem pemerintahan negara yang berlaku untuk seluruh
wilayah negara, dan itu artinya tidak ada istilah negara lain selain Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman tersebut sejalan dengan
Penjelasan Pasal 18 tersebut, bahwa “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu
eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya
yang bersifat staat juga”.
2. Negara
Hukum Indonesia.
Sebelum
membahas bagaimana konsep negara hukum Indonesia, baiknya kita lihat dahulu
konsepsi negara hukum itu sendiri. Konsep Negara hukum secara historis beranjak
dari pemikiran Plato pada masa Yunani kuno, yakni dalam karyanya yang berjudul Nomoi.
Plato berpandangan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang
didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tersebut dikuatkan
oleh Aristoteles dalam karyanya berjudul Politica, bahwa suatu negara
yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan
hukum. Ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yakni :
“…pertama,
pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan
dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan
hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan
konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang
dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang
dilaksanakan pemerintahan despotik.”
Substansi
utama dari konsep negara hukum adalah bahwa sebuah negara dan sistem
pemerintahan negara haruslah dijalankan dengan berlandaskan pada hukum yang
berkedaulatan rakyat, dan oleh karenanya maka penggunaan kekuasaan oleh
pemerintah tidak boleh melampaui, menyalahi dan bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
3. Konsep
Negara Hukum Pancasila.
Istilah
Negara Hukum Pancasila lahir dan digunakan untuk memberi penegasan bahwa
landasan ideologis dan falsafati dibentuknya NHI (Negara Hukum Indonesia)
adalah nilai luhur pancasila yang telah ditempatkan sebagai satu dasar negara (PhilosophischeGrondslag),
sebagaimana tersebut dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar
negara, Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, kuat dan
tetap serta tidak dapat diubah dengan cara apapun, berkedudukan sebagai
landasan bagi menetapkan tata hukum dan pemerintahan di indonesia.
Kendatipun
bekas jajahan Belanda dan pernah menjalankan hukum kolonial, namun tidak serta
merta dapat dikatakan bahwa konsep negara hukumnya identik Belanda, karena
secara historis dan filosofis kelahiran Indonesia berbeda dengan Belanda.
Karena Indonesia sebagai sebuah negara sejak lahir sudah anti penindasan dan
kesewenangan.
Dengan
mengkaji konteks historical-philosophic yang meliputi keberadaan
Indonesia merdeka, Negara Hukum Pancasila sebagai konsep yang khas Indonesia
dan berbeda dari konsepsi lain baik itu rechtsstaat maupun the rule of law,
menurut Philipus M. Hadjon
memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar, yakni diantaranya :
1. Jika dalam konsep rule of law dan rechtsstaat
menempatkan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai titik
sentralnya, maka bagi bangsa Indonesia yang tidak menghendaki faham
liberal-individualistic, titik sentral dari Negara Hukum Pancasila adalah
keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan
(kekeluargaan/gotong royong).
2. Jika dalam rangka perlindungan HAM konsep rule
of law mengedepankan prinsip “equality before the law”, dan prinsip
“rechtmatigheid” untuk rechtsstaat, maka konsep pancasila mengedepankan
“asas kerukunan” untuk menjaga keserasian serta keselarasan hubungan antara
penguasa dengan rakyatnya, dimana dari asas tersebut diharapkan nantinya
terjalin hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan
negara.
3. Konsep Pancasila lebih mengedepankan musyawarah
untuk mufakat dalam tiap penyelesaian sengketa, dengan meletakkan penyelesaian
melalui jalur peradilan sebagai langkah terakhir.
Negara
hukum pancasila dalam pandangan Soepomo merupakan aktualisasi dari cita negara
Integralistik, yang terdiri unsur-unsur sebagai karakteristik dari konsep
bernegara pancasila, yakni; pertama, kesatu paduan antar elemen
kenegaraan untuk mencapai (keseimbangan hidup) lahir dan batin (asas kerukunan);
kedua, tidak diterimanya faham pemisahan antara negara (pemerintah) dan
individu (rakyat), dan antar kekuasaan pemerintahan; ketiga,
pemerintahan tidak dijalankan secara sentralistik dan otoriter; keempat,
kedaulatan adalah ditangan rakyat, dalam artian sistem hukum dan konstitusi
haruslah timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya; kelima, negara
berkewajiban mengurus dan mengusahakan terwujudnya apa yang menjadi cita-cita
luhur rakyat; keenam, pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman
suku bangsa, ras dan bahasa, dimana tata pemerintahan dibangun diatas integrasi
(harmoni) keberagaman dan atas dasar kekhasan dan keaslian indonesia sebagai
sebuah bangsa.
Moh.
Hatta dalam pidatonya secara tersirat menggambarkan cita negara hukum Indonesia
sebagai sebuah konsep negara pengurus, yakni:
“memang
kita harus menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar
gotong royong dan hasil usaha bersama … Akan tetapi kita mendirikan negara yang
baru. hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita buat
jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita
membangun masyarakat baru yang berdasarkan kepada gotong royong, usaha bersama,
tujuan kita adalah membarui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita
memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan diatas
negara baru suatu negara kekuasaan….kedaulatan rakyat yang kita temui di dalam
majelis permusyawaratan rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada presiden, ialah
presiden jangan sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan…ada baiknya jaminan
diberikan kepada rakyat hak merdeka berpikir.”
Pandangan
Moh. Hatta tersebut menitik beratkan pada perlunya jaminan terhadap penegakan
dan penghormatan Hak-hak dasar warga negara, yang harus dengan jelas
dicantumkan secara tertulis dan pada ruang tersendiri dalam Konstitusi negara,
dimana pencantuman Hak-hak dasar tersebut nantinya diharapkan akan menjadi
landasan bagi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak
kesewenang-wenangan penguasa yang dimungkinkan hadir.
Philipus
M. Hadjon dalam desertasinya menjelaskan bahwa Negara Hukum Pancasila secara
elementer berpegang pada beberapa prinsip dasar sebagai berikut :
1. Hubungan antara rakyat dengan pemerintah
berdasarkan asas kerukunan. Asas kerukunan adalah perwujudan dari jiwa dan
spirit kebangsaan Indonesia yang dibangun diatas kebersamaan (komunalisme)
bukan individualisme, yang menonjolkan budaya gotong royong dan kekeluargaan
diantara elemen kebangsaan, sehingga yang hendak dicapai dari adanya demokrasi
dan negara berdasar hukum adalah keserasian/ keseimbangan hubungan antara
pemerintah dan rakyat.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara
kekuasaan-kekuasaan negara. Jalannya kekuasaan negara tidak menganut sistem
pemisahan kekuasaan yang bersifat rigid dan tegas, namun lebih sebagai bentuk
pembagian kekuasaan, sehingga antara kekuasaanyang satu dengan kekuasaan lain
dalam praktek pemerintahan terjalin suatu hubungan fungsional yang proporsional
dan selaras. Prinsip ini secara mendasar tidak memerlukan sistem check and
balances, karena dengan pola hubungan yang fungsional proporsional
tersebut, setiap proses berpemerintahan dan berkebijakan akan senantiasa
melalui mekanisme permusyawaratan sebagai mekanisme asli bangsa Indonesia.
3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan
peradilan merupakan sarana terakhir. Pemahaman ini beranjak pada asas kerukunan yang
dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan, dimana
permusyawaratan adalah cara bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalahnya.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pola
pandang bangsa yang komunalistik menjadikan bangsa Indonesia lebih mendahulukan
untuk terlaksananya kewajiban dari pada hak.
4.
Demokrasi dan Good Governance.
Menyimak
bahasan diatas, dapat dilihat bahwa antara demokrasi dan negara hukum memiliki
keterkaitan yang erat, karena disatu sisi konsep negara hukum diadakan dan
dijalankan dalam rangka menjamin adanya tata pemerintahan demokratis di suatu
negara, disisi lain sebuah negara hukum mendasarkan dirinya dan tata
sistemiknya pada asas-asas dan prinsi-prinsip demokrasi guna menjamin
legitimasinya.
Demokrasi
yang didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat sesungguhnya bermuara pada
usaha untuk menciptakan tata pemerintahan negara yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia, dengan mengedepankan perlunya partisipasi sebesar mungkin warga
dalam proses kepemerintahan negara sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat,
adalah sebuah konsep yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan
letak dimana demokrasi itu hendak dipraktekkan.
J.B.J.M
Ten berge secara umum mengemukakan prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai
berikut :
1.
Perwakilan politik. Keputusan politik tertinggi
diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum.
2.
Pertanggungjawaban politik. Organ pemerintahan
dalam menjalankan fungsinya bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan.
3.
Pemencaran kewenangan guna mengantisipasi agar
tidak adanya diktatorial.
4.
Pengawasan dan kontrol. Prinsip bahwa pelaksanaan
pemerintahan harus dapat dikontrol.
5.
Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.s
6.
Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan
keberatan.
2.
Konstitusi
2.1.
Pengertian
Konstitusi berasal dari kata constitution, constitutie,
constituer, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa
indonesi akonstitusi diterjemahkan atau disamakan dengan UUD. Konstitusi
menurut makna katanya berarti dasar suatu susunan suatu badan politik yang
disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan
suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau
memerintah negara. Peraturan – peraturan ada yang tertulis sebagai keputusan
badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi.
Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa ada dua
pengertian konstitusi, yaitu;
a.
Dalam
arti luas
Merupakan
suatu keseluruhan atura atau ketentuan dasar (hukum dasar yang mengikuti hukum
dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu
pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara).
b.
Dalam
arti sempit
Merupakan
undang –undang dasar yang berisi aturan- aturan dan ketentuan – ketentuan yang
bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara.
Sedangkan konstitualisme menurut soetandio
wingjosoebroto adalah pembetasan kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga
negara, tidak hanya terdapat sesamanya namun juga yerhadap hak kebebasan warga
negara pada asasnya terbatas, sedangkan hak warga negara pada asasnya tidak
terbatas pembatasnya, apabila diperukan hanay bisa dilakukan berdasakan
kesepakatan para warga negara sendiri, lewat suatu proses yang dilaksanaka
dalam suasana yang bebas. Jadi antara konstituasi dengan konstitualisme sangat
erat hubungannya , jika knstitusi merupakan dasar atau landasan yang digunakan
oleh suatu negara, maka konstitualisme merupakan sebuah paham atau ajaran
tentang tata cara atau proses dalam pembahasan hak- hak kodrati warga negara
yang ada didala konstituasi iru sendiri.
2.2.
Tujuan Konstitusi
Menurut CF. Strong , tujuan konstitusi adalah
membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang
diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan
konstitusi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan
yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah
tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam
konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan
perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal
konstitusi.
Tujuan-
tujuan adanya konstitusi secara ringkas
dapat diklarifikasikan menjadi tiga. Diantaranya adalah sebagai berikut:
a.
Konstitusi
bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasanm terhadap kekuasaan
politik.
b.
Konstitusi
bertujuan untuk melepaskan control kekuasaan dari penguasaan sendiri.
c.
Konstitusi
bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya.
2.3.
Fungsi Konstitusi
Konstitusi memiliki fungsi yang
berperan dalam suatu negara. Fungsi Konstitusi adalah sebagai berikut:
a. Konstitusi berfungsi
membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kewenang-wenangan yang
dilakukan oleh pemerintahan agar hak-hak bagi warga negara perlindungan dan
tersalurkan (konstitusionalsme) .
b. Konstitusi berfungsi sebagai
piagam kelahiran suatu negara.
c. Konstitusi berfungsi sebagai
hukum tertinggi.
d. Konstitusi berfungsi sebagai
alaat yang membatasi kekuasaan.
e. Konstitusi berfungsi sebagai
identitas nasional dan lambing.
f. Konstitusi berfungsi
senbagai perlindungan hak asasi manusia
dan kebebasaan warga negara.
2.4.
Lahirnya
Konstitusi di Indonesia
Sebagai negara yang berdasarkan
hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan
undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang
sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum baagi
pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.
Latar belakang terbentuknya
konstitusi (UUD 1945) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan
bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi “sejak
dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah
mulai berusaha membalsakan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia
Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara,
untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda.
Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku
memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta memimbing bangsa
Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas disemua bidaang, sehingga diharapkan
kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sendiri sebagai bangsa Asia
Timur raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu
lebih lam menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah menyerah
tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan luas untuk
berbulat dan tidak bergantung pada jepang sampai saat kemerdekaan tiba.
Setelah kemerdekaan diraih,
Kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tdak bisa ditawar-tawarkan
lagi, dan segera harus dirumuska. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah
negara yang derdaulat. Pada tanggal 18 agustus 1945 atau sehari setelah ikrar
kemerdekaan, Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan siding
yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagaai berikut:
1. Mengesahkan
dan menetapkan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang – undang
yang dirumuskan oleh panitia perumusan pada tanggal 22 Juni 1945.
2. Menetapkan
dan mengesahkan UUD1945 yang bahanya hampir seluruh diambil dari RUU yang
disusun oleh paanitia perancang UUd tanggal 16 juni 1945.
3. Memiliki
ketua persiapan kemerdekaan indoneia Ir, soekarno sebagai presiden dan wakil
ketua Drs. Muhammad Hatta sebgai wakil presiden.
4. Pekerjaan
presiden untuk sementara waktu dibantu oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
yang kemudian menjadi komitmen Nasional.
Dengan terpilihnya Presiden dan
wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia
sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap
negra telah ada yaitu adanya :
a. Rakyat yaitu Indonesia.
b. Wilayah yaitu tanah air Indonesia
yang terbentang dari sabang hingga merauke yang terdiri dari 13:500 buah pulau
besar dan kecil.
c. Kedaulatan yaitu sejak mengucap
proklamasi kemerdekaan Indonesia.
d. Pemerintahan yaitu sejak terpilihnya
presiden dan wakil sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara.
e. Tujuan negara yaitu mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.
f. Bentuk negara yaitu negara kesatuan.
2.5.
Bentuk Konstitusi Negara Indonesia
Dalam buku “ K.C Wheare
modern constitution ( 1975)” menyatakan bentuk konstitusi adalah sebagai
berikut:
1. Konstitusi
tertulis dan konstitusi tidak tertulis ( written constitution and unwritten
constitution).
Ø Konstitusi tertulis
adalah konstitusi yang diletakkan dalam suatu naskah tertentu. Ada beberapa
keuntungan konstitusi, yaitu :
a. Organisasi
Negara itu dapat terjamin, dalam arti tidak berubah sewaktu-waktu jadi tidak
tunduk kepada kehendak orang tertentu.
b. Adanya
pedoman tertentu untuk perkembangan lebih lanjud. Misalnya pada suautu pasal
atau bab, sehingga prkambangan biasa dikembalikan pada norma tertentu.
Ø Konstitusi tidak
Tertulis adalah konstitusi yang tidak diletakkan dalam suatu naskah tertentu. Namun ada pula beberapa
kelemahan tidak adanya naskah (konstitusi tidak tertulis). Misalnya dalam
menentukan siapa yang berwenang menentukan bahwa kebiasaan yang baru dalam masyarakat yang
merupakan hukum yang baru. Karena tidak adanya naskah tertentu, bagaimana kita
dapat mengetahui adanya keadaan yang baru yang bertentangan dengan naskah itu.
Di inggris hal ini dipecahkan dalam memberi wewenang pada parlemen yang disebut
omnipotence, yaitu wewenang tertinggi disegala hal pada parlemen.
2.
Konstitusi
fleksibel dan konstitusi rigid ( flexible and rigid constitution).
Ø Konstitusi fleksibel
yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain :
a.
Sifat
elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah,
b. Dinyatakan
dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang.
Ø Konstitusi rigid
mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain :
a.
Memiliki
tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang,
b.
Hanya
dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa.
3. Konstitusi
derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Konstitusi derajat
tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan
peraturan perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah
konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama.
4. Konstitusi
negara serikat dan negara kesatuan. Bentuk negara akan sangat
menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat
terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan
negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian
kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena
pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.
5. Konstitusi
pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan
presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain :
ØPresiden memiliki
kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai
Kepala Pemerintahan,
Ø Presiden dipilih langsung
oleh rakyat atau dewan pemilih,
Ø Presiden tidak termasuk
pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum
Konstitusi dalam sistem
pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri (Sri Soemantri) :
Ø Kabinet dipimpin oleh
seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai
parlemen,
Ø Anggota kabinet sebagian
atau seluruhnya dari anggota parlemen,
Ø Presiden dengan saran
atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan
diadakan pemilihan umum.
Konstitusi dengan
ciri-ciri seperti itu oleh Wheare disebut “Konstitusi sistem pemerintahan
parlementer”. Menurut Sri Soemantri, UUD 1945 tidak termasuk ke dalam kedua
konstitusi di atas. Hal ini karena di dalam UUD 1945 terdapat ciri konstitusi
pemerintahan presidensial, juga terdapat ciri konstitusi pemerintahan
parlementer. Pemerintahan Indonesia adalah sistem campuran.
2.6.
Peranan Konstitusi dalam Kehidupan
Bernegara
Sejauh mana
konstitusi – yang diterjemahkan dalam UUD – berperan terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara? Terhadap pertanyaan itu pada umum nya ada 3 sudut
pandang berserta argumentasinya masing- masing
Pandangan yang pertama beranggapan bahwa setiap negara memiliki konstitusi,
namun konstitusi tidak boleh dipandang sebagai segalanya.
Konstitusi memang memuat ketentuan atau aturan dasar, ditulis dan disusun
secara runtut (UUD Tertulis) ataupun hanya didasarkan pada catatan berdasarkan
adat atau kebiasaan (konvensi) namun toh ia memerlukan penterjemahan dalam
bentuk aturan yang lebih jelas yang bernama Undang Undang (UU) Berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam negara demokrasi , lebih
ditentukan oleh kadar kesadaran masyarakat akan nilai-nilai demokrasi itu
sendiri. masyarakat, pada umumnya kurang peduli terhadap pemerintahan macam
apa, yang akan dihasilkan pemilu. Tidak sedikit diantaranya bahkan alergi atau
sinis terhadap dunia politik. Hal yang bisa ditenggarai dari rendahnya
partisipasi politik dalam pemilu yang umumnya hanya diikuti sekitar enam puluh
persen dari rakyat pemilih. Masyarakat lebih memilih tetap menekuni bidang
kerja masing-masing ketimbang ikut dalam kegiatan politik. Banyak negara
demokrasi yang tanpa harus mengutak atik konstitusinya dapat menjalani
kehidupan berbangsa dan bernegara secara normal dan tertib.
Pandangan kedua menganggap, konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara
dalam penyelenggaraan negara, dan yang terpenting bagi negara adalah
penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa dan taat hukum.
Penyelenggaraan negara hanya akan baik apabila pimpinan di strata manapun
memberikan contoh melalui perbuatan dan tindakan nyata. Yang diperlukan negara
adalah figur pemimpin yang kuat dan memiliki integritas. Tujuan negara adalah
mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Penganut pandangan ini lebih
melihat tegaknya hukum sebagai prasyarat berjalan nya kehidupan berbangsa dan
bernegara. Demokrasi dianggap hanyalah alat mencapai tujuan negara artinya
demokrasi bukan tujuan. Namun pandangan kedua
ini harus menghadapi
kenyataan bahwa negara yang lebih menggantungkan pemerintahan pada figur kuat
pemimpin umumnya menghadapi kendala saat tiba pada pelaksanaan suksesi
kepemimpinan.
Pandangan yang ketiga, konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan
bernegara. Apabila negara memiliki konstitusi yang normal kehidupan
berbangsa dan bernegarapun dapat berlangsung. Mungkin saja masyarakat dalam
suatu negara demokrasi tidak lagi mempersoalkan konstitusi harus dilihat dari sudut
pandang bahwa konstitusi negara tersebut memang memenuhi syarat sebagai
konstitusi yang baik yang oleh karenanya diterima dengan baik pula oleh
warganya. Konstitusi yang demokratik biasanya memuat tiga hal yakni
tercantumnya prinsip2 dasar HAM, adanya lembaga-lembaga tinggi negara dan
kejelasan batasan fungsi dan kewenangan dan hubungan antar lembaga.
Di samping itu, yang tentu tidak
kalah pentingnya ialah peranan Pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, dan
lembaga-lembaga penyiaran. Pemerintah lah yang menguasai lebih banyak
informasi, sumber-sumber dana, sarana, dan prasarana, tenaga, keahlian, dan jaringan
yang dapat diharapkan mendukung upaya pemasyarakatan dan pendidikan konstitusi.
Karena itu, tanggungjawab utama dan pertama untuk pemasyarakatan dan pendidikan
konstitusi itu ada di tangan Pemerintah. Setelah Pemerintah sungguh-sungguh
menjalankan perannya baru lah kita dapat berharap bahwa lembaga-lembaga
pendidikan dan lembaga-lembaga penyiaran dapat digerakkan untuk berperan aktif
dalam upaya pendidikan dan pemasyarakatan mengenai pentingnya kehidupan
bernegara yang berdasarkan konstitusi.
Demikian pula masyarakat sendiri,
tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga swadaya masyarakat,
organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan semua institusi yang berperan dalam
lingkungan masyarakat madani (civil society), dalam lingkungan dunia usaha atau
business (market), dan dalam lingkungan organ-organ negara, organ-organ daerah
secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sudah seharusnya secara sinergi
mendukung, membantu, dan memprakarsai berbagai upaya untuk menyukseskan
kegiatan pemasyarakatan dan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Dengan begitu,
kita dapat berharap bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 akan benar-benar menjadi “living consttution”, sehingga tugas
konstitusional Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai “the guardian and the sole
interpreter of the constitution” menjadi lebih mudah diwujudkan.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa
konstitusi merupakan acuan tertulis yang digunakan untuk menjalankan negara
dalam hal ini bisa perundang-undangan. Dan mahkamah konstitusi lah yang
bertanggungjawab untuk mengatur jalannya konstitusi tersebut sesuai dengan apa
yang sudah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui, kenyataannya justru pemerintah
dan masyarakat itu sendiri lah yang kerap melanggar konstitusi. Oleh karena
itu, sangat diharapkan kita sebagai warga negara yang baik dapat
sungguh-sungguh menyadari dan sekaligus mengerti arti pentingnya Mahkamah
Konstitusi dalam rangka mewujudkan jaminan-jaminan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban
konstitusional mereka sendiri dalam kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945.
Kesimpulan :
Negara
adalah organisasi tertinggi diantara sekelompok atau beberapa kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah
tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Bentuk negara ada dua
menurut susunannya yaitu, Negara kesatuan dan Negara federasi. Untuk Indonesia
sendiri telah menegaskan dirinya dalam konstitusi negara sebagai sebuah Negara
kesatuan yang berbentuk republik.
Konstitusi merupakan acuan tertulis yang digunakan untuk
menjalankan negara dalam hal ini bisa perundang-undangan. Indonesia memiliki konstitusi yang
dikenal dengan undang-undang dasar 1945. Dan mahkamah konstitusi lah yang
bertanggungjawab untuk mengatur jalannya konstitusi tersebut sesuai dengan apa
yang sudah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui, kenyataannya justru pemerintah
dan masyarakat itu sendiri lah yang kerap melanggar konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA
Effendy,
HAM. 1993. Falsafah Negara Pancasila (sejarah, fungsi, pengamalan dan
pelestariannya) Cet. Ketiga. Semarang : Duta Grafika.
H.R.,
Ridwan. 2007. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Jakarta : Raja Grafindo Press.
Hardani,
Muhammad. 2003. Konstitusi-konstitusi Modern. Surabaya : Pustaka Eureka.
Jennings, Sir Ivor. 1979. The Law
and The Constitution. Fifth edition.London : Holderand Stoughton.
Ranadireksa,
Hendarmin. 2007. Visi Bernegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa ada
negara yang gagal melaksanakan demokras. Bandung : Fokusmedia.
Rozak, Abdul. 2004. Buku Suplemen
Pendidikan Kewarganegaraan (civic education), Jakarta : ICCE UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation.
Sorensen,
Georg. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi (proses dan prospek dalam sebuah dunia
yang sedang berubah), Alih bahasa: I Made Krisna. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Thaib
, Dahlan , dkk. 2005. Teori konstitusi dan hukum konstitusi cet kelima. jakarta.
Yamin,
Muhammad. 1959. Naskah Persiapan UUD 1945, jilid I. Jakarta : Yayasan
Prapanca.
Yamin,
Muh. 1945. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.
Yamin,
Muh.1960. Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tjipanas.
Hendarmin
Ranadireksa, Visi Bernegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa ada
negara yang gagal melaksanakan demokrasi, Fokusmedia, Bandung, 2007, hal. 58-59
Muh.
Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, 1945, hal.
236-238
H.
Muhammad Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tjipanas,
1960, hal. 286-288.
Ridwan
H.R., HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2007, hal. 2.
HAM
Effendy, Falsafah Negara Pancasila (sejarah, fungsi, pengamalan dan
pelestariannya), Cet. ketiga, Duta Grafika, Semarang, 1993, hal. 37.
Philipus
M. Hadjon, 1987, Op.Cit, hal. 84.
Muhammad
Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, jilid I, Yayasan Prapanca, Jakarta,
1959. hal.110-115.
Philipus
M. Hadjon, Op.cit, hal. 85-90.
Georg
Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi (proses dan prospek dalam sebuah dunia
yang sedang berubah), Alih bahasa: I Made Krisna, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2003, hal. 15.
Ridwan
H.R., 2007, Op. Cit, hal. 10.
Jennings, Sir Ivor.
The Law and The Constitution. Fifth edition.London : Holderand Stoughton,1979.
Hal 34-35
Hardani, Muhammad.
Konstitusi-konstitusi Modern, Surabaya : Pustaka Eureka,2003. Hal 35
Rozak,
Abdul, 2004, Buku Suplemen Pendidikan Kewarganegaraan (civic education),
Jakarta : ICCE UIN S yarif Hidayatullah Jakarta dan The Asia F oundation. Hal
57
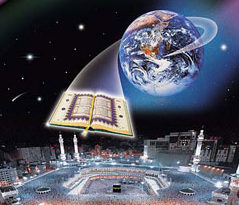


Comments
Post a Comment